Politik Indonesia Sepanjang Sejarah di Rangkum Unpacking
Upackingindonesia - Panggung politik Indonesia tak pernah sepi. Sejak kelahirannya, ia telah menjadi arena bagi drama-drama besar yang penuh dengan idealisme, intrik, kompromi, dan konflik. Babak-babaknya berganti dengan cepat, seringkali tak terduga, didorong oleh para aktor dengan ideologi yang saling bertentangan, namun berbagi panggung yang sama: sebuah bangsa yang tengah mencari bentuknya. Ini adalah sebuah cerita tentang perjalanan panjang, sebuah narasi tentang bagaimana sebuah gagasan bernama "Indonesia" diperjuangkan, diperdebatkan, dan dipertaruhkan dari masa ke masa.
Untuk memahami denyut nadi politik Indonesia hari ini, kita harus menengok kembali ke belakang, menarik benang-benang merah yang menjalin setiap era menjadi sebuah permadani sejarah yang utuh. Ada beberapa benang utama yang akan kita ikuti. Pertama, tarik-ulur abadi antara sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan desakan otonomi dari daerah-daerah yang merasa dianaktirikan. Kedua, perdebatan yang tak pernah usai tentang peran Islam dalam kehidupan bernegara—apakah ia menjadi sumber inspirasi atau landasan formal. Ketiga, peran unik dan seringkali dominan militer, yang lahir dari rahim revolusi dan merasa memiliki hak untuk ikut mengatur jalannya pemerintahan. Keempat, ayunan pendulum sejarah antara euforia demokrasi yang penuh kebebasan dan kerinduan akan stabilitas yang seringkali berujung pada cengkeraman otoritarianisme. Dan terakhir, bagaimana kondisi ekonomi hampir selalu menjadi bahan bakar yang menyulut api perubahan politik besar.
Laporan ini akan membawa Anda menyusuri lorong waktu, dari fajar kesadaran nasional di awal abad ke-20, melalui eksperimen demokrasi yang bergejolak, masuk ke dalam era otoriter yang panjang dan stabil namun rapuh, hingga ledakan reformasi yang membuka gerbang demokrasi modern beserta segala tantangannya. Ini bukan sekadar rangkaian tanggal dan peristiwa, melainkan sebuah upaya untuk merangkai cerita yang saling terhubung, memahami "mengapa" di balik "apa", dan melihat bagaimana drama di panggung politik Indonesia terus berlanjut hingga hari ini, di sebuah persimpangan jalan yang menentukan masa depannya.
Bab 1: Benih Ditanam: Lahirnya Kesadaran Nasional (1908-1945)
Di awal abad ke-20, Hindia Belanda adalah sebuah masyarakat kolonial yang mapan, namun di bawah permukaannya yang tenang, benih-benih perubahan mulai bertunas. Secara tak sengaja, pemerintah kolonial sendiri yang menyiraminya. Kebijakan Politik Etis, yang bertujuan "membalas budi" dengan menyediakan pendidikan bagi kaum pribumi, justru melahirkan sebilah pedang bermata dua: sebuah generasi baru kaum terpelajar yang tercerahkan.
Tiga Jalan Menuju Indonesia: Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij
Jika pergerakan nasional diibaratkan sebuah orkestra, maka ada tiga komponis utama di babak awal yang masing-masing membawa warna musik yang berbeda, namun kelak menyatu dalam simfoni kebangsaan.
Budi Utomo (1908): Sang Pelopor yang Santun
Lahir pada 20 Mei 1908, Budi Utomo adalah sang pembuka jalan. Didirikan oleh dr. Soetomo dan para mahasiswa sekolah kedokteran STOVIA di Batavia, organisasi ini terinspirasi oleh gagasan mulia dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Jawa untuk menggalang dana beasiswa bagi pelajar pribumi berprestasi.
Sarekat Islam (1912): Raksasa Pergerakan Massa
Jika Budi Utomo bersifat elitis, Sarekat Islam (SI) adalah gelombang pasang dari rakyat jelata. Akarnya adalah Sarekat Dagang Islam (SDI), yang didirikan di Surakarta sekitar tahun 1905-1909 untuk melindungi para pedagang batik pribumi dari persaingan dengan pedagang Tionghoa.
Indische Partij (1912): Sang Pendobrak yang Radikal
Berbeda dengan Budi Utomo yang kultural dan SI yang berbasis massa-agama, Indische Partij (IP) adalah partai politik murni pertama yang tanpa tedeng aling-aling meneriakkan kata "merdeka". Didirikan oleh Tiga Serangkai—Ernest Douwes Dekker (Danudirja Setiabudi), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara)—IP mengusung gagasan radikal pada masanya.
“Indie voor Indiers” (Hindia untuk Orang Hindia), menyerukan persatuan semua ras dan golongan yang menganggap Hindia sebagai tanah airnya untuk melawan diskriminasi kolonial.
De Express, seperti artikel Suwardi yang legendaris, “Als ik eens Nederlander was” (Andai Aku Seorang Belanda), mereka menyerang jantung sistem kolonial. Sikap non-kooperatif dan radikal ini membuat pemerintah Belanda gerah. Tak butuh waktu lama, pada 1913, partai ini dibubarkan dan ketiga pemimpinnya diasingkan.
Dari tiga jalan yang berbeda ini—pendidikan, massa-agama, dan politik radikal—terlihat jelas DNA politik Indonesia yang akan terus berkembang. Sejak awal, telah ada tiga aliran pemikiran utama yang saling bersaing dan terkadang beririsan: nasionalisme yang berorientasi pada kebudayaan dan kenegaraan, politik yang berlandaskan identitas Islam, serta ideologi kiri yang fokus pada perjuangan kelas. Sejarah politik Indonesia selanjutnya, dalam banyak hal, adalah panggung bagi interaksi, koalisi, dan konflik di antara ketiga "DNA" ini.
Puncak Kristalisasi: Sumpah Pemuda (1928)
Semangat kebangsaan yang ditabur oleh berbagai organisasi itu akhirnya menemukan momen puncaknya. Jika sebelumnya perjuangan masih banyak diwarnai sentimen kedaerahan, seperti yang tecermin dari nama-nama organisasi pemuda (Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Celebes, dll.)
Mereka mengaku: bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Perdebatan Dasar Negara di BPUPKI/PPKI
Ketika kemerdekaan sudah di depan mata pada 1945, para pendiri bangsa dihadapkan pada pertanyaan paling fundamental: di atas dasar apa negara baru ini akan didirikan? Dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), perdebatan sengit pun terjadi, terutama antara dua golongan utama: Nasionalis-Islam dan Nasionalis-Sekuler.
Golongan Nasionalis-Islam, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, berpendapat bahwa negara Indonesia seharusnya berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Puncak dari perjuangan mereka adalah lahirnya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang pada sila pertamanya memuat kalimat: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Namun, tujuh kata ini menimbulkan kekhawatiran. Sesaat setelah proklamasi, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut Jepang yang menyampaikan aspirasi dari tokoh-tokoh Kristen di Indonesia Timur. Mereka menyatakan keberatan atas kalimat tersebut dan mengancam tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia jika kalimat itu dipertahankan.
Keputusan ini adalah contoh pertama dari sebuah pola yang akan menjadi ciri khas politik Indonesia: kompromi ideologis demi menjaga persatuan nasional. Para pendiri bangsa, dihadapkan pada pilihan antara negara dengan dasar ideologi formal yang berisiko terpecah atau negara kesatuan yang utuh di atas dasar yang lebih inklusif, mereka memilih yang kedua. Seperti yang dikisahkan oleh KH Masjkur, para tokoh Islam saat itu merasa lebih baik mengambil musammah (substansi atau esensi) nilai-nilai Islam dalam Pancasila daripada memaksakan isim (nama atau bentuk formal) negara Islam yang bisa memecah belah bangsa.
Bab 2: Eksperimen Pertama: Jatuh Bangun Demokrasi Parlementer (1949-1959)
Setelah proklamasi kemerdekaan dan perjuangan fisik mempertahankan kedaulatan, Indonesia memasuki babak baru: sebuah eksperimen besar dalam berdemokrasi. Mengadopsi model dari Eropa, para pemimpin bangsa memilih sistem demokrasi parlementer, sebuah sistem di mana pusat kekuasaan berada di parlemen, dan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat.
Selamat Datang Demokrasi Liberal
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Indonesia menjadi panggung bagi pertarungan ide-ide politik yang bebas.
Festival Demokrasi dan Pesta Golongan: Pemilu 1955
Di tengah ketidakstabilan itu, Indonesia berhasil menyelenggarakan sebuah hajatan demokrasi yang monumental: Pemilihan Umum 1955. Pemilu ini hingga kini dikenang sebagai yang paling bebas, jujur, dan demokratis dalam sejarah Indonesia.
Hasil pemilu secara gamblang memetakan kekuatan politik riil di masyarakat, yang ternyata terfragmentasi ke dalam empat kutub ideologis utama.
Tabel: Hasil Pemilu 1955 untuk DPR dan Konstituante (4 Besar)
Tabel di atas menunjukkan sebuah paradoks. Di satu sisi, pemilu berhasil menjadi cermin aspirasi rakyat yang sangat beragam. Namun di sisi lain, hasil yang begitu terfragmentasi ini justru menjadi sumber kelumpuhan politik. Tidak ada satu pun partai yang mampu membentuk pemerintahan yang kuat sendirian. Koalisi yang dibangun pun sangat rentan karena perbedaan ideologi yang mendasar, terutama antara partai-partai Islam (Masyumi dan NU) dengan PKI. Keberhasilan prosedural pemilu justru menelanjangi kebuntuan substansial dalam politik Indonesia saat itu.
Badai di Daerah: Pemberontakan PRRI/Permesta
Sementara para politisi di Jakarta sibuk berebut kuasa, di daerah-daerah, api ketidakpuasan mulai menyala. Banyak tokoh militer dan sipil di Sumatera dan Sulawesi merasa bahwa pemerintah pusat terlalu Jawa-sentris dan tidak adil dalam mengalokasikan dana pembangunan.
Pada awal 1958, mereka memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Penting untuk dicatat, tuntutan utama mereka bukanlah untuk memisahkan diri dari Indonesia, melainkan untuk menuntut otonomi yang lebih luas, pembubaran kabinet yang dianggap pro-komunis, dan kepemimpinan nasional yang lebih adil.
Jalan Buntu di Konstituante dan Lahirnya Dekrit
Di saat yang bersamaan, Dewan Konstituante yang diharapkan bisa melahirkan UUD baru justru menemui jalan buntu. Setelah bersidang selama lebih dari dua tahun, para anggotanya gagal mencapai kesepakatan mengenai dasar negara.
Kombinasi dari tiga krisis—instabilitas politik di tingkat pusat, pemberontakan di daerah, dan kebuntuan di Konstituante—menciptakan situasi darurat yang membahayakan kelangsungan negara. Kondisi inilah yang menjadi justifikasi bagi Presiden Soekarno untuk turun tangan secara langsung. Dengan dukungan dari militer, pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden yang isinya sangat fundamental
Pembubaran Konstituante.
Pemberlakuan kembali UUD 1945.
Tidak berlakunya lagi UUDS 1950.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).
Dekrit ini menandai akhir dari eksperimen demokrasi parlementer di Indonesia. Pintu menuju sistem yang lebih otoriter telah terbuka lebar. Era ini mengajarkan sebuah pelajaran pahit: demokrasi bukan hanya tentang kebebasan dan pemilu, tetapi juga tentang kemampuan untuk mengelola perbedaan dan menghasilkan pemerintahan yang efektif. Ketika institusi demokrasi gagal melakukannya, ia menjadi rentan terhadap keruntuhannya sendiri.
Bab 3: Di Bawah Komando "Pemimpin Besar Revolusi": Era Demokrasi Terpimpin (1959-1966)
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bukan sekadar pergantian konstitusi, melainkan sebuah tikungan tajam dalam perjalanan politik Indonesia. Babak demokrasi liberal yang riuh rendah dan penuh ketidakpastian ditutup, digantikan oleh sebuah era baru yang disebut Demokrasi Terpimpin. Ini adalah era di mana panggung politik didominasi oleh satu aktor utama: Presiden Soekarno, sang "Pemimpin Besar Revolusi".
Konsep dan Filosofi Demokrasi Terpimpin
Bagi Soekarno, Demokrasi Parlementer adalah produk impor dari Barat yang terbukti gagal dan tidak cocok dengan "jiwa" bangsa Indonesia.
Tiga Pilar Kekuasaan: NASAKOM
Untuk menjalankan Demokrasi Terpimpin, Soekarno membangun sebuah arsitektur politik yang bertumpu pada tiga pilar kekuatan ideologis yang ia yakini mewakili seluruh elemen bangsa. Arsitektur ini dikenal dengan akronim NASAKOM: Nasionalisme, Agama, dan Komunisme.
Kebangkitan PKI: Era ini menjadi panggung utama bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah kepemimpinan D.N. Aidit. Dengan mendukung penuh konsep Demokrasi Terpimpin dan NASAKOM, PKI berhasil mendapatkan legitimasi dan perlindungan langsung dari Presiden Soekarno.
Peran TNI AD sebagai Penyeimbang: Di sisi lain, Angkatan Darat (TNI AD) memandang kebangkitan PKI dengan penuh kecurigaan dan permusuhan.
Soekarno sebagai Penyeimbang: Di tengah-tengah dua kekuatan yang saling bermusuhan ini, berdirilah Soekarno. Ia memainkan peran sebagai penyeimbang, menggunakan PKI untuk mengimbangi kekuatan militer yang terkadang terlalu mandiri, dan sebaliknya, menggunakan militer untuk menjaga agar PKI tidak terlalu dominan. Sistem politik NASAKOM pada dasarnya adalah sebuah politik keseimbangan yang sangat rapuh, yang sepenuhnya bergantung pada wibawa dan kemampuan manuver Soekarno. Selama Soekarno kuat, keseimbangan ini bisa terjaga. Namun, di bawah permukaan, persaingan antara TNI AD dan PKI terus memanas, menciptakan sebuah "bom waktu" politik.
Politik Luar Negeri yang Konfrontatif
Semangat revolusi yang berapi-api di dalam negeri juga tecermin dalam politik luar negeri Indonesia. Soekarno memposisikan Indonesia sebagai pemimpin kekuatan "Dunia Ketiga" atau New Emerging Forces (NEFOS) yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Puncak dari kebijakan ini adalah Konfrontasi "Ganyang Malaysia".
Klimaks dari sikap konfrontatif ini adalah keputusan dramatis Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Januari 1965.
Klimaks Berdarah: Peristiwa G30S 1965
Bom waktu politik yang telah lama terpasang akhirnya meledak pada malam tanggal 30 September 1965. Sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September, yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dari Batalyon Cakrabirawa (pasukan pengawal presiden), melakukan aksi penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal senior Angkatan Darat.
Dalam kekosongan pimpinan Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), dengan cepat mengambil alih komando.
Peristiwa G30S menjadi titik balik yang menghancurkan seluruh bangunan Demokrasi Terpimpin. PKI sebagai salah satu pilar utama hancur lebur. Kekuasaan dan legitimasi Soekarno terkikis habis karena dianggap terlalu dekat dengan PKI.
Bab 4: Stabilitas di Atas Segalanya: Rezim Orde Baru (1966-1998)
Runtuhnya Demokrasi Terpimpin dalam tragedi G30S 1965 membuka jalan bagi babak baru yang akan berlangsung selama 32 tahun: era Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto. Lahir dari trauma atas kekacauan politik dan kemerosotan ekonomi di era sebelumnya, rezim ini dibangun di atas satu kredo utama: stabilitas adalah segalanya. Orde Baru adalah sebuah antitesis dari era Soekarno; jika sebelumnya panggung politik dipenuhi hiruk pikuk ideologi, maka Soeharto secara sistematis meredamnya demi fokus pada pembangunan ekonomi.
Lahirnya Orde Baru
Transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto berjalan secara bertahap namun pasti. Kuncinya adalah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966. Dokumen misterius ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengambil "segala tindakan yang dianggap perlu" guna memulihkan keamanan dan ketertiban.
Arsitektur Kekuasaan Orde Baru
Soeharto membangun sebuah arsitektur kekuasaan yang kokoh dan terpusat, yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaannya dan menjamin stabilitas. Terdapat tiga pilar utama yang menopang rezim ini.
Trilogi Pembangunan sebagai Ideologi: Orde Baru menawarkan sebuah "kontrak sosial" baru kepada rakyat. Sebagai ganti dari partisipasi politik, pemerintah menjanjikan pembangunan dan kesejahteraan. Ideologi ini dirumuskan dalam Trilogi Pembangunan: (1) Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis, (2) Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya.
Penyederhanaan Partai Politik (Fusi Parpol 1973): Untuk menghilangkan "penyakit" persaingan ideologis yang dianggap sebagai sumber kekacauan di masa lalu, Soeharto melakukan kebijakan depolitisasi secara masif. Pada tahun 1973, sembilan partai politik yang ada dipaksa untuk melebur (fusi) menjadi hanya dua partai: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai wadah partai-partai Islam (NU, Parmusi, PSII, Perti), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai wadah partai-partai nasionalis dan non-Islam (PNI, Partai Katolik, Murba, dll.).
Golongan Karya (Golkar), yang secara teknis bukan partai, melainkan "kendaraan politik" pemerintah yang didukung penuh oleh birokrasi dan militer. Dengan format 2 partai dan 1 Golkar ini, kompetisi politik menjadi semu. Pemilu diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun, namun hasilnya sudah bisa ditebak: Golkar selalu menjadi pemenang mutlak.
Dwifungsi ABRI sebagai Tulang Punggung: Pilar ketiga dan yang paling vital adalah militer. Konsep Dwifungsi ABRI, yang dicetuskan oleh Jenderal A.H. Nasution, dilembagakan secara penuh oleh Soeharto.
Ketiga pilar ini ditopang oleh sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Semua keputusan penting diambil di Jakarta, sementara daerah hanya menjadi pelaksana kebijakan pusat. Inisiatif lokal dimatikan, dan kekayaan sumber daya alam daerah banyak dieksploitasi untuk kepentingan pusat, yang pada gilirannya memicu kembali benih-benih ketidakpuasan daerah.
Keberhasilan dan Sisi Gelap
Selama lebih dari dua dekade, formula Orde Baru tampak berhasil. Stabilitas politik tercapai, dan ekonomi tumbuh pesat. Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada pertengahan 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) sukses menekan laju pertumbuhan penduduk, angka buta huruf menurun drastis, dan pendapatan per kapita meningkat secara signifikan.
Namun, di balik fasad stabilitas dan pembangunan, terdapat sisi gelap yang mengerikan. Stabilitas dicapai melalui represi. Kebebasan pers dibungkam, kritik terhadap pemerintah dianggap subversif, dan aktivis mahasiswa diawasi dengan ketat.
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merajalela, melibatkan keluarga dan kroni-kroni presiden.
Runtuhnya Rezim
Fondasi legitimasi Orde Baru yang dibangun di atas keberhasilan ekonomi ternyata sangat rapuh. Ketika Krisis Moneter melanda Asia pada 1997, Indonesia menjadi negara yang paling parah terkena dampaknya.
Krisis ekonomi dengan cepat berubah menjadi krisis kepercayaan. Rakyat yang selama ini diam karena perutnya kenyang, kini mulai marah. "Kontrak sosial" Orde Baru telah berakhir. Mahasiswa kembali turun ke jalan dalam gelombang demonstrasi yang masif, menuntut reformasi total.
Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, di mana empat mahasiswa tewas tertembak oleh aparat, yang kemudian menyulut kerusuhan besar di Jakarta dan kota-kota lain.
Bab 5: Pintu Reformasi Terbuka Lebar (1998-Sekarang)
Lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh gejolak dan harapan: Era Reformasi. Digerakkan oleh kekuatan mahasiswa dan didukung oleh rakyat yang muak dengan krisis multidimensi, gelombang perubahan ini bertujuan untuk membongkar total warisan otoriter Orde Baru dan membangun kembali fondasi negara di atas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.
Euforia Reformasi dan 6 Agenda Utama
Semangat perubahan meledak di seluruh negeri. Para mahasiswa yang menduduki kompleks gedung DPR/MPR menjadi simbol dari kekuatan rakyat yang tak lagi bisa dibendung.
Agenda Reformasi 1998, yang menjadi cetak biru bagi perubahan-perubahan fundamental yang akan datang
Adili Soeharto dan kroni-kroninya: Menuntut pertanggungjawaban hukum atas praktik KKN dan pelanggaran HAM selama 32 tahun kekuasaannya.
Amandemen UUD 1945: Mengubah konstitusi yang dianggap terlalu memberikan kekuasaan tak terbatas kepada presiden dan tidak menjamin HAM.
Hapuskan Dwifungsi ABRI: Mengembalikan militer ke barak dan memisahkannya dari panggung politik praktis.
Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya: Mengakhiri sentralisasi kekuasaan dan memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Tegakkan supremasi hukum: Memastikan hukum berlaku adil untuk semua, tidak lagi menjadi alat kekuasaan.
Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN: Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga ke akarnya.
Agenda ini, pada dasarnya, adalah sebuah reaksi total terhadap semua "dosa" Orde Baru. Setiap pilar Reformasi adalah antitesis langsung dari pilar-pilar kekuasaan rezim sebelumnya.
Membangun Ulang Fondasi Negara
Di bawah kepemimpinan transisional Presiden B.J. Habibie, yang menggantikan Soeharto, keran-keran demokrasi dibuka lebar.
Amandemen UUD 1945 (1999-2002): Ini adalah pilar reformasi yang paling mendasar. Melalui empat tahap amandemen yang dilakukan oleh MPR antara tahun 1999 dan 2002, "aturan main" politik Indonesia dirombak total.
Tabel: Ringkasan Amandemen UUD 1945 (1999-2002) | Amandemen | Tanggal Pengesahan | Perubahan Utama | | :--- | :--- | :--- | | Pertama | 19 Oktober 1999 | - Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden (maksimal 2 periode).
- Pergeseran kekuasaan legislasi dari Presiden ke DPR.
| Kedua | 18 Agustus 2000 | - Pengakuan dan pengaturan Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).
- Penambahan bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Pemisahan struktur TNI dan Polri.
- Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
- Mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden/Wakil Presiden.
| Keempat | 10 Agustus 2002 | - Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
- Penegasan tentang pendidikan dan kebudayaan, serta perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
| Ketiga | 10 November 2001 | - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Reformasi TNI: Tuntutan penghapusan Dwifungsi ABRI dijawab. Secara bertahap, peran sosial-politik militer dihilangkan. Fraksi TNI/Polri di parlemen dibubarkan pada 2004, dan anggota militer aktif dilarang menduduki jabatan sipil.
Kebebasan Pers: Salah satu perubahan paling dramatis adalah di bidang kebebasan berekspresi. Pemerintahan Habibie mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang selama Orde Baru menjadi momok bagi media.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Sebagai jawaban langsung atas tuntutan reformasi dan trauma sentralisasi Orde Baru, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Undang-undang ini, yang kemudian direvisi beberapa kali, menandai pergeseran paradigma radikal dari sentralisasi ke desentralisasi.
Kehidupan Politik Pasca-Reformasi
Panggung politik Indonesia berubah total. Sistem multipartai yang bebas kembali hidup. Pemilu 1999, yang pertama di era reformasi, diikuti oleh 48 partai politik.
Di tengah perubahan besar ini, peran tokoh-tokoh kunci menjadi sangat penting. B.J. Habibie dikenang sebagai presiden transisi yang dalam waktu singkat meletakkan fondasi-fondasi demokrasi.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi simbol penegakan supremasi sipil atas militer dan pembelaan terhadap pluralisme serta hak-hak minoritas.
Amien Rais, sebagai salah satu motor utama gerakan reformasi, memimpin MPR dalam proses amandemen UUD 1945.
Sutan Sjahrir dengan gagasan diplomasi dan sosialisme-demokratisnya
Mohammad Hatta dengan konsep demokrasi ekonomi dan koperasinya, kembali menjadi relevan dalam wacana pembangunan bangsa.
Adnan Buyung Nasution menjadi ikon perjuangan bantuan hukum dan HAM melalui LBH
Namun, reformasi juga membawa konsekuensi yang tidak terduga. Meskipun institusi-institusi baru seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk, penyakit lama seperti korupsi tidak hilang. Ia hanya berpindah tempat. Otonomi daerah yang luas, tanpa diimbangi pengawasan yang kuat, justru "mendesentralisasikan" korupsi dan melahirkan "raja-raja kecil" di daerah.
Penutup: Demokrasi Indonesia, Mau ke Mana?
Perjalanan politik Indonesia selama lebih dari satu abad adalah sebuah epik yang memukau. Dari benih-benih kesadaran yang ditanam di awal abad ke-20 hingga hiruk pikuk demokrasi digital abad ke-21, panggung politik bangsa ini telah menyaksikan segalanya. Jika kita merangkum seluruh drama ini, akan terlihat sebuah dialektika yang terus-menerus antara tiga tarikan kekuatan utama: dorongan untuk mewujudkan persatuan nasional dalam sebuah negara yang sangat beragam, hasrat untuk menjalankan partisipasi demokratis yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, dan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan agar pembangunan dapat berjalan. Setiap era dalam sejarah Indonesia, pada hakikatnya, adalah sebuah upaya—terkadang berhasil, seringkali gagal—untuk menemukan titik keseimbangan yang pas di antara ketiga tarikan tersebut.
Era Pergerakan Nasional adalah tentang menemukan identitas bersama. Demokrasi Parlementer adalah eksperimen partisipasi yang mengorbankan stabilitas. Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru adalah pendulum yang berayun ke arah sebaliknya, mengorbankan partisipasi demi stabilitas dan persatuan versi penguasa. Era Reformasi adalah upaya besar-besaran untuk mengembalikan partisipasi demokratis dan menata ulang konsep persatuan melalui desentralisasi.
Kini, setelah lebih dari dua dekade Reformasi, Indonesia kembali berada di persimpangan jalan. Fondasi demokrasi telah dibangun: pemilu berjalan rutin dan damai, kebebasan pers relatif terjamin, masyarakat sipil aktif, dan militer telah kembali ke peran profesionalnya.
Pertama, polarisasi dan politik identitas telah menjadi hantu baru yang menakutkan. Penggunaan isu agama dan suku untuk kepentingan elektoral, yang mengemuka tajam sejak beberapa pemilu terakhir, telah membelah masyarakat secara tajam dan merusak tenun kebangsaan yang dirajut dengan susah payah oleh para pendiri bangsa.
Ketiga, muncul kekhawatiran serius tentang kemunduran demokrasi (democratic backsliding). Pelemahan lembaga-lembaga independen seperti KPK, dugaan intervensi terhadap lembaga yudikatif, dan menguatnya kembali cengkeraman oligarki politik dan ekonomi menjadi sinyal-sinyal yang meresahkan.
masyarakat sipil—termasuk mahasiswa, aktivis, dan media independen—menjadi semakin krusial sebagai benteng terakhir penjaga demokrasi, yang terus menyuarakan kritik dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.
Sejarah telah menunjukkan bahwa perjalanan politik Indonesia tidak pernah linear. Ia bergerak dalam siklus, berayun seperti pendulum antara ekstrem kebebasan dan ekstrem stabilitas. Pertanyaan besarnya kini adalah, ke mana pendulum ini akan berayun selanjutnya? Apakah Indonesia, dengan segala pelajaran pahit dari masa lalunya, akan mampu mengatasi tantangan-tantangan kontemporer ini untuk memperdalam kualitas demokrasinya? Ataukah, dalam menghadapi ketidakpastian global dan polarisasi domestik, kerinduan akan "stabilitas" akan kembali membuka jalan bagi bentuk-bentuk otoritarianisme baru? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan nasib 270 juta lebih rakyat Indonesia, tetapi juga akan menjadi pelajaran penting bagi dunia tentang perjuangan sebuah bangsa besar dalam merawat demokrasinya. Panggung ini belum akan sepi, dan babak selanjutnya sedang ditulis.



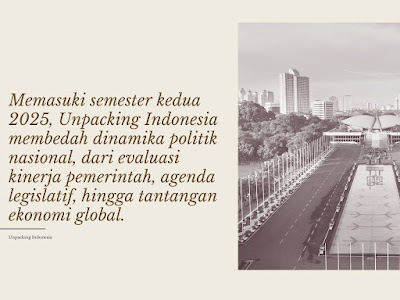

Komentar
Posting Komentar